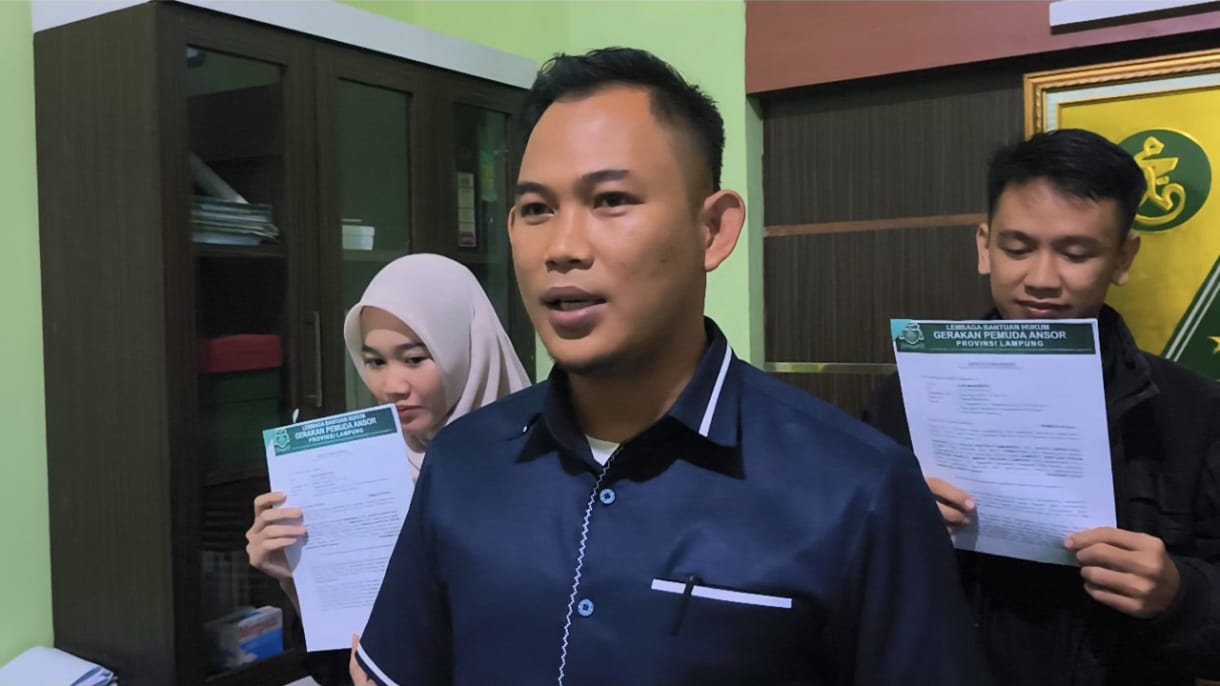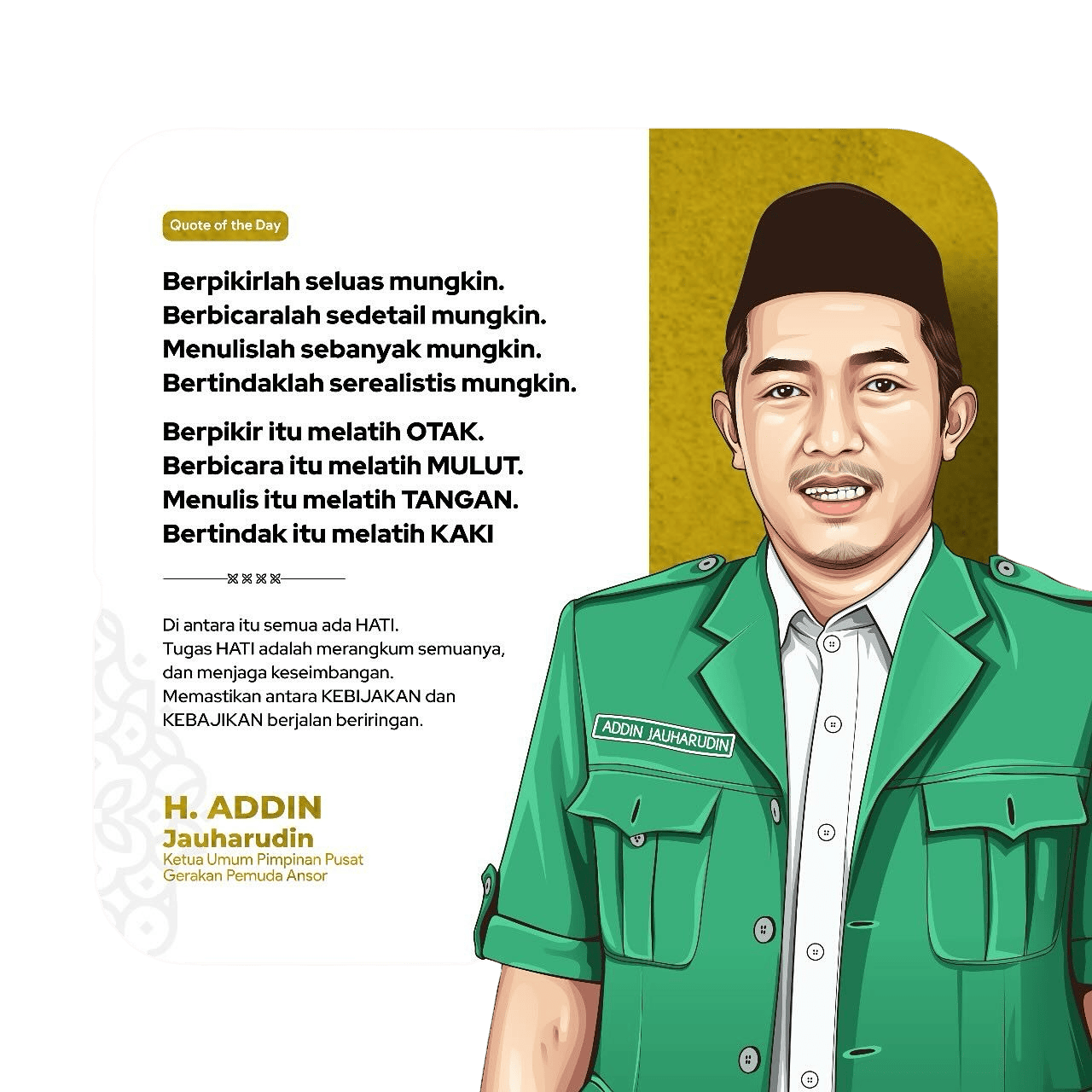Nanggroe Aceh, yang sejak lama dikenal sebagai Serambi Mekah, punya peran penting dalam sejarah peradaban Islam di Nusantara. Sebagai pintu gerbang penyebaran Islam, wilayah ini tidak hanya menjadi saksi masuknya agama Islam tetapi juga lahirnya ulama-ulama besar. Di antara tokoh ulama tersebut, nama Syekh Abdurrauf As-Singkili menonjol sebagai seorang cendekiawan moderat yang menjembatani antara tasawuf dan syariat.
Lahir pada tahun 1024 Hijriah atau 1615 Masehi di Fansur, Singkil, sebuah kawasan di pantai barat Laut Aceh, sekarang Kabupaten Aceh Singkil. Syekh Abdurrauf tumbuh di lingkungan yang kental dengan tradisi keislaman. Tempat kelahirannya, Fansur, dikenal sebagai pusat intelektual pada masa itu. Ayah dan para ulama di sekitarnya menjadi guru pertamanya, memberikan fondasi kuat bagi pengembangan ilmu agama yang kelak menjadi bekal pengembaraan intelektual yang panjang.
Pada usia muda, Syekh Abdurrauf memutuskan untuk melanjutkan pencarian ilmu hingga ke jazirah Arab. Pada tahun 1642, ia memulai perjalanan haji sekaligus menimba ilmu, singgah di Doha, Yaman, Jeddah, hingga akhirnya bermukim di Mekah dan Madinah. Selama 19 tahun, ia menyesap ilmu kepada 19 guru dan 27 ulama ternama, memperkaya pengetahuannya dalam berbagai bidang, mulai dari fikih hingga tasawuf.
Salah satu gurunya yang paling berpengaruh adalah Ahmad al-Qusyasyi, seorang ulama besar di Madinah. Di bawah bimbingan al-Qusyasyi, Syekh Abdurrauf mendalami tasawuf dan mendapatkan ijazah untuk menyebarkan tarekat Syattariyah dan Qadiriyah di Nusantara. Setelah wafatnya al-Qusyasyi, ia melanjutkan belajar kepada Ibrahim al-Kurani pengarang kitab Ithaf Al-Dhaki, yang memperluas wawasannya dalam bidang ilmu eksoteris seperti tafsir dan hadis. Gabungan kedua guru besar ini membentuk keilmuan yang mendalam pada diri Syekh Abdurrauf, menjadikannya seorang ulama yang mumpuni dalam ilmu lahir maupun batin.
Kontroversi Ajarah Wahdatul Wujud
Saat Syekh Abdurrauf masih muda, wilayah Kesultanan Aceh tengah dilanda kontroversi pemikiran teologis yang tajam. Pertentangan terjadi antara kelompok wujudiyah yang dipimpin oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani dengan kelompok anti-wujudiyah yang diketuai Nuruddin ar-Raniri. Perbedaan pandangan ini tidak hanya berakhir pada perdebatan, tetapi juga berujung pada pembakaran buku-buku Hamzah Fansuri dan penganiayaan terhadap para pengikutnya.
Kontroversi ini meninggalkan perenungan yang mendalam pada pemikiran Syekh Abdurrauf. Ketika ia kembali ke Aceh pada tahun 1661, situasi di tanah kelahirannya membutuhkan pendekatan yang lebih moderat dan harmonis. Dalam kapasitasnya sebagai Qadhi Malik al-Adil atau mufti pada masa Sultanah Safiatuddin (1645-1675), ia berusaha memadukan dan mendamaikan unsur-unsur tasawuf dan syariat, menciptakan harmoni di tengah perbedaan.
Warisan Keilmuan yang Abadi
Salah satu kontribusi terbesar Syekh Abdurrauf adalah karya-karyanya yang mencakup berbagai disiplin ilmu. Tafsir Tarjuman al-Mustafid, karyanya yang paling terkenal, menjadi tafsir pertama Al-Quran dalam bahasa Melayu. Tafsir ini tidak hanya memudahkan pemahaman ajaran Islam bagi masyarakat Melayu, tetapi juga menjadi rujukan penting dalam studi Islam Nusantara.
Selain itu, ia menulis Tanbih al-Masyi al-Mansub ila Tariq al-Qusyasyiy, sebuah karya yang membahas konsep wahdatul wujud dengan pendekatan yang lebih hati-hati sekaligus sebagai jawaban pertikaian pemikiran teologis wujudiyah tanpa mendiskreditkan pihak manapun. Melalui karya ini, ia menjelaskan bahwa tasawuf bukanlah ancaman terhadap syariat, tetapi sebuah jalan untuk memperkuat pemahaman terhadap agama Islam yang lebih mendalam.
Pemikiran Syekh Abdurrauf yang menekankan harmoni antara tasawuf dan syariat tetap relevan hingga saat ini. Di tengah masyarakat yang sering kali terpecah oleh perbedaan pandangan dan pemikiran, pendekatannya memberikan pelajaran penting tentang moderasi. Ia menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah alasan untuk berkonflik, tetapi peluang untuk saling melengkapi.
Warisan Syekh Abdurrauf tidak hanya menjadi bagian penting dari sejarah Islam di Nusantara, tetapi juga inspirasi bagi generasi masa kini. Perjalanan panjangnya dalam menuntut ilmu, perjuangannya di tanah kelahiran, dan kontribusinya dalam literatur Islam adalah bukti bahwa intelektualitas dan spiritualitas dapat berjalan beriringan, menciptakan peradaban yang lebih baik.
Oleh : Ahmad Darojatun