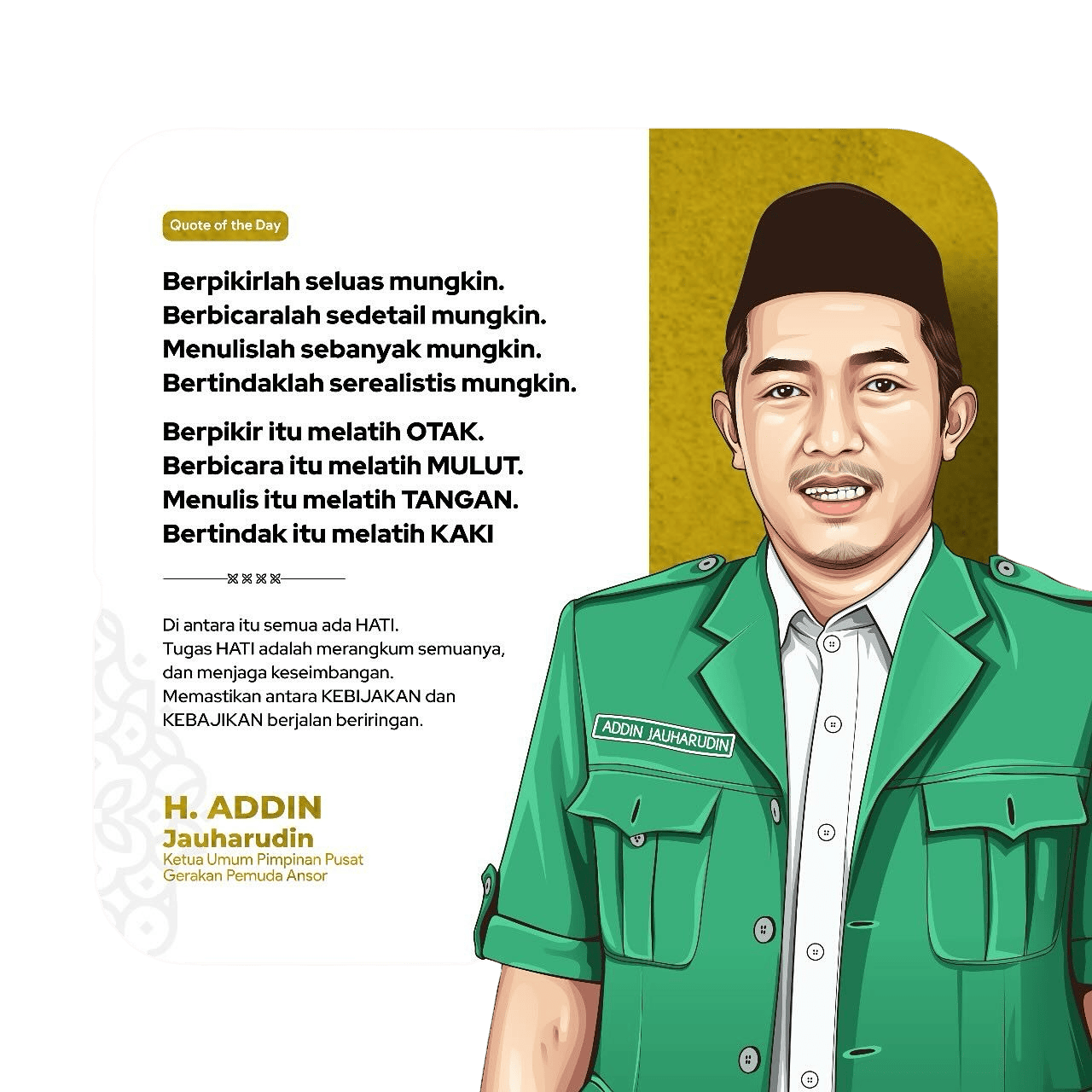OPINI - Di tengah laju zaman yang serba cepat dan tidak menentu, pragmatisme semakin menjadi pendekatan yang menonjol dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari pengambilan keputusan politik, strategi bisnis, hingga kehidupan personal, prinsip-prinsip pragmatis cenderung diutamakan dibandingkan idealisme yang dianggap kerap terlalu utopis. Pragmatisme, sebagai pendekatan yang berfokus pada efektivitas dan hasil nyata, tampaknya menjadi respons paling logis terhadap kompleksitas dunia modern yang penuh dinamika dan ketidakpastian.
Secara historis, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang berkembang di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Tokoh-tokohnya seperti Charles Sanders Peirce, William James, dan John Dewey menekankan bahwa nilai sebuah ide ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Filsafat ini menolak pendekatan absolut dan lebih menekankan pada apa yang “berfungsi” dalam konteks tertentu. Di era saat ini, tanpa disadari, pandangan semacam ini meresap ke dalam hampir setiap keputusan masyarakat modern.
Di bidang politik, pragmatisme tampil sebagai strategi dominan, terutama di negara-negara demokrasi yang mengalami fragmentasi kepentingan. Para politisi cenderung memilih kebijakan yang dapat diterima oleh mayoritas publik atau elite kekuasaan, ketimbang mendorong agenda ideologis yang bisa menimbulkan resistensi besar. Ini bisa dilihat dari bagaimana isu-isu seperti perubahan iklim, reformasi hukum, dan pembangunan ekonomi seringkali didekati dengan kompromi demi kelangsungan kekuasaan atau stabilitas pemerintahan.
Namun, pragmatisme dalam politik juga mengandung paradoks. Di satu sisi, ia memungkinkan kemajuan yang realistis dan mencegah konflik berkepanjangan. Di sisi lain, pragmatisme yang berlebihan bisa melumpuhkan visi besar dan meminggirkan prinsip moral. Dalam banyak kasus, kepentingan jangka pendek akhirnya mengalahkan kepentingan jangka panjang. Misalnya, kebijakan yang merusak lingkungan bisa tetap diteruskan karena secara praktis menguntungkan secara ekonomi dalam jangka pendek.
Dalam dunia bisnis, pragmatisme adalah landasan utama dalam pengambilan keputusan. Perusahaan tidak lagi bertumpu pada visi idealis semata, melainkan pada angka, efisiensi, dan hasil yang terukur. Inovasi dihargai selama menghasilkan keuntungan, dan loyalitas terhadap nilai-nilai sering kali dikorbankan demi fleksibilitas dan adaptabilitas pasar. Strategi seperti outsourcing, pivot bisnis, hingga keputusan untuk merger-acquisition didasari oleh perhitungan pragmatis ketimbang etika atau loyalitas pada tenaga kerja.
Pragmatisme juga menjalar ke dalam kehidupan sosial dan personal. Generasi muda saat ini, yang tumbuh dalam ketidakstabilan ekonomi dan cepatnya perubahan sosial, cenderung lebih memilih keputusan hidup berdasarkan “apa yang masuk akal sekarang” dibandingkan ideal-ideal tradisional. Hal ini tampak pada pola relasi, karier, bahkan pandangan terhadap keluarga dan pernikahan. Prinsip “jalan tengah yang efektif” lebih dipilih daripada mempertahankan nilai yang mungkin sudah tidak relevan dalam konteks zaman.
Media sosial mempercepat penyebaran semangat pragmatis ini. Platform digital menuntut respons cepat, konten ringkas, dan hasil instan. Di sinilah pragmatisme menjadi sangat dominan—yang penting viral, bukan benar; yang penting berpengaruh, bukan mendalam. Influencer dan tokoh publik yang sukses adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan tren, bukan yang bertahan pada orisinalitas atau nilai pribadi yang kaku.
Namun, pragmatisme bukan tanpa kritik. Salah satu tantangan utamanya adalah mengaburkan batas antara “apa yang bisa dilakukan” dan “apa yang seharusnya dilakukan.” Dalam banyak kasus, tindakan pragmatis tidak selalu adil atau benar secara moral. Ketika efektivitas menjadi satu-satunya tolok ukur, nilai-nilai seperti keadilan, empati, dan solidaritas bisa terpinggirkan. Ini membuat pragmatisme rentan disalahgunakan sebagai pembenaran untuk keputusan oportunis.
Selain itu, pragmatisme yang terlalu dominan dapat melemahkan daya juang terhadap perubahan yang bersifat struktural. Misalnya, jika semua pihak hanya bertindak pragmatis, siapa yang akan memperjuangkan reformasi mendalam yang mungkin butuh waktu lama dan pengorbanan besar? Di sinilah idealisme masih memegang peranan penting sebagai penyeimbang pragmatisme, agar masyarakat tidak terjebak dalam rutinitas kompromi yang stagnan.
Meski demikian, pragmatisme tetap relevan dan bahkan penting dalam dunia yang semakin kompleks. Dunia yang terus berubah membutuhkan fleksibilitas dalam berpikir dan bertindak. Selama pragmatisme dijalankan dengan kesadaran etis dan tujuan yang benar, ia bisa menjadi alat yang efektif untuk mencapai kemajuan. Pragmatisme bukan musuh dari nilai-nilai luhur, tetapi justru bisa menjadi jembatan antara realitas dan cita-cita.
Keseimbangan antara pragmatisme dan idealisme adalah kunci. Kita membutuhkan orang-orang yang mampu berpikir realistis sekaligus tetap setia pada prinsip. Dalam konteks ini, pragmatisme seharusnya tidak dilihat sebagai bentuk kepengecutan moral, tetapi sebagai bentuk kecerdasan kontekstual—kemampuan untuk memilih strategi yang paling efektif dalam kerangka nilai yang tetap dijaga.
Di era saat ini, sikap pragmatis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Namun, kebutuhan ini tidak boleh membutakan kita dari pertanyaan-pertanyaan mendasar: Apakah yang kita lakukan benar? Apakah hasil yang dicapai sepadan dengan konsekuensinya? Apakah kita masih memiliki arah, atau hanya sekadar bertahan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang harus terus dihadirkan sebagai koreksi terhadap pragmatisme yang bisa saja menjelma menjadi ketidakpedulian sistemik.
Akhirnya, kita perlu mengingat bahwa pragmatisme hanyalah alat, bukan tujuan. Ia harus diarahkan oleh visi dan nilai. Di tengah realitas yang keras dan menuntut, manusia tetap membutuhkan harapan, keyakinan, dan arah yang melampaui sekadar “apa yang berhasil.” Pragmatisme yang bijak adalah pragmatisme yang tahu kapan harus fleksibel, dan kapan harus teguh.