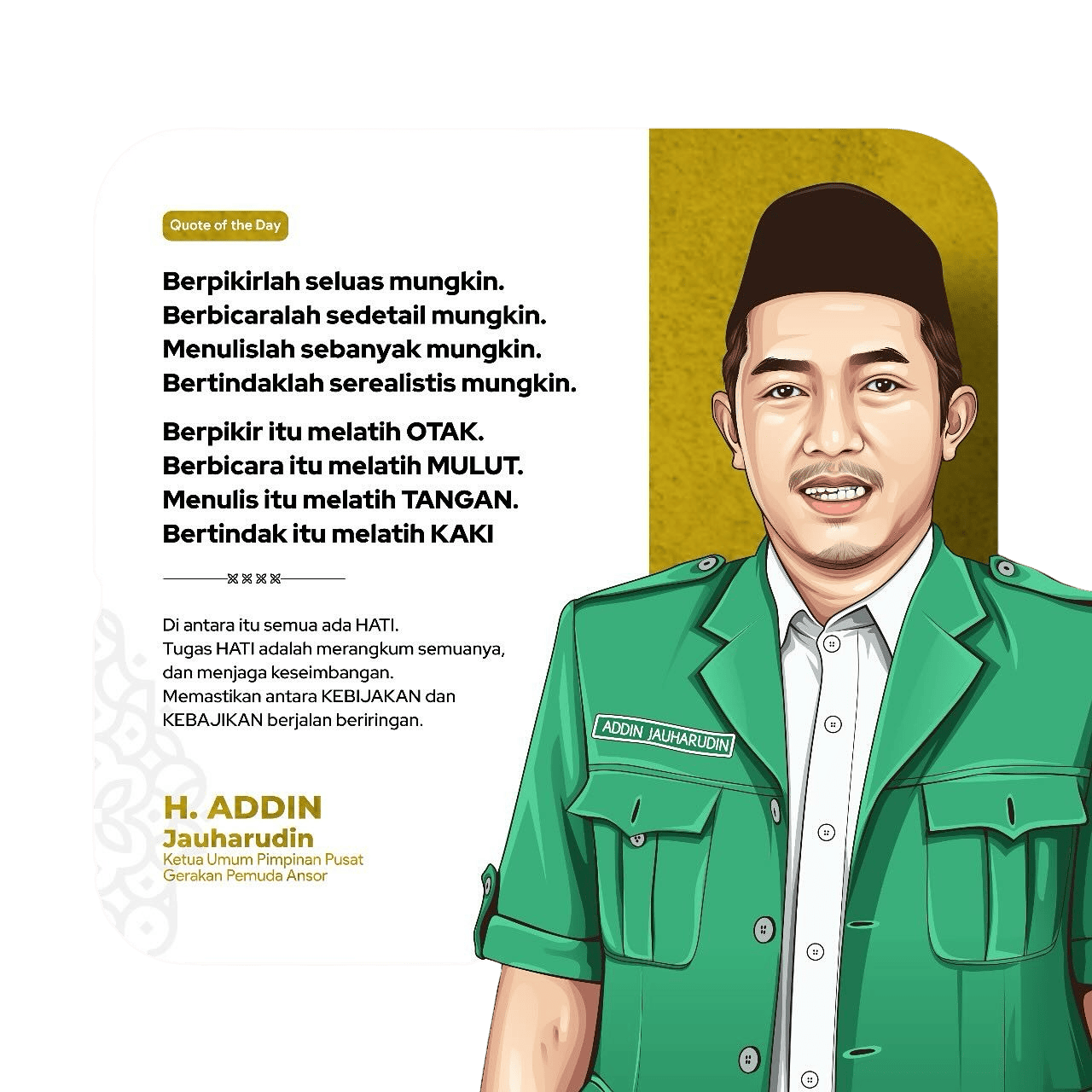OPINI - Di setiap nafas kehidupan, nama Tuhan selalu hadir. Ia disebut dalam doa pagi yang lirih, dalam jerit permohonan saat malam sepi, dalam ucapan syukur, maupun dalam ratapan yang nyaris tanpa suara. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa Tuhan adalah tempat kembali, tempat berlindung, dan tempat semua jiwa bertumpu ketika dunia tak memberi jawab.
Namun dalam kenyataan yang kita saksikan hari ini, ada sesuatu yang ganjil. Tuhan disebut semakin sering, tetapi wajah manusia semakin kabur. Nama-Nya terdengar di ruang publik, media, bahkan dalam aturan hukum. Tapi justru dalam keramaian itu, suara orang-orang kecil, yang berbeda, yang minor, yang terpinggirkan, makin nyaris tak terdengar. Seolah dalam bayang-bayang kemuliaan Tuhan, keberadaan mereka tak lagi penting.
Agama yang seharusnya membimbing manusia menjadi lebih lembut, justru kadang menjelma menjadi instrumen keras yang memukul tanpa peringatan. Semua dibenarkan dengan kalimat sakti: “Ini perintah Tuhan.” Maka manusia berhenti bertanya, berhenti mendengar, dan mulai menuding. Ruang diskusi ditutup rapat-rapat, karena kebenaran sudah dianggap selesai dideklarasikan—oleh segelintir yang merasa paling tahu isi langit.
Ironisnya, Tuhan yang Mahabesar itu sering kali dipersempit oleh manusia menjadi slogan, menjadi dalil pembenar, menjadi alat penghakiman. Padahal, bukankah keagungan-Nya justru tak terbatas? Apakah Ia perlu dibela dengan menghardik sesama? Apakah Ia memerlukan manusia untuk menegakkan kemuliaan-Nya dengan menyingkirkan yang tak sama?
Kita hidup di zaman ketika simbol-simbol agama menjulang tinggi, tapi rasa iba pada sesama justru menghilang dari pandangan. Rumah ibadah dibangun megah, tapi tetangga yang berbeda keyakinan tak disapa. Kitab suci dibaca fasih, tapi hati mengeras saat berhadapan dengan perbedaan. Bukankah keimanan seharusnya membuat hati menjadi lebih ringan, bukan lebih berat oleh kecurigaan?
Toleransi bukan sekadar membiarkan, tapi memahami. Ia tidak lahir dari rasa takut, tapi dari keberanian untuk menerima bahwa dunia memang diciptakan penuh warna. Namun sering kali, justru dalam nama Tuhan, warna-warna itu dipaksa menjadi satu. Keberagaman dianggap sebagai gangguan terhadap ketertiban iman. Padahal bukankah semesta ini sengaja diciptakan dengan segala macam bentuk, suku, dan bahasa?
Dalam banyak kasus, agama dijadikan pagar yang tinggi dan tajam. Hanya mereka yang mirip yang boleh masuk. Yang berbeda diminta berdiri di luar, atau jika perlu, dibungkam. Padahal tidak ada satu pun manusia yang mampu mewakili Tuhan secara sempurna. Bahkan mereka yang paling fasih beragama pun tetap manusia—penuh celah dan terbatas.
Kita pun menyaksikan bagaimana manusia yang datang dengan membawa kasih, justru dicurigai. Yang berbicara damai dianggap abu-abu. Yang mencoba menengahi dianggap lemah. Seolah kekuatan iman kini hanya diukur dari seberapa keras suara kita membantah, bukan seberapa dalam kita mampu memahami.
Ketika manusia semakin merasa mewakili Tuhan, bahaya justru mengintai: kita mulai kehilangan kemampuan untuk meraba derita orang lain. Kita sibuk memastikan langit tak tercemar, tapi tak pernah menengok bumi yang retak. Kita bicara tentang surga, sambil menciptakan neraka kecil bagi mereka yang tidak sepaham.
Yang lebih menyedihkan, sering kali yang paling keras membela Tuhan, justru yang paling jauh dari kelembutan-Nya. Lidahnya fasih menyebut nama Tuhan, tapi matanya tak mampu menatap penderitaan. Ia sibuk menertibkan moral orang lain, tapi tak punya waktu menyeka air mata manusia yang terluka oleh sistem yang sama sekali tidak adil.
Padahal, jika kita berhenti sejenak dan mendengarkan, suara Tuhan justru paling nyaring terdengar lewat jeritan manusia yang disakiti, lewat doa orang yang ditolak, lewat air mata mereka yang terusir atas nama iman. Tuhan, kalau boleh memilih, mungkin lebih ingin kita melindungi satu jiwa yang lemah daripada membangun seribu monumen yang menyebut nama-Nya.
Agama seharusnya menjadi jalan pulang, bukan pagar yang mengurung. Ia seharusnya mengajarkan kita untuk melihat wajah Tuhan di wajah siapa saja, tak peduli dari mana asalnya, bagaimana doanya, atau apa keyakinannya. Tapi kini, kita terlalu sibuk mengukur kesalehan, sampai lupa bertanya: apakah hati kita masih mampu merasa?
Semakin sering Tuhan diklaim, semakin rawan manusia diabaikan. Kita mulai lebih takut dianggap menyimpang daripada menyakiti. Kita lebih rajin menuduh bid’ah daripada mengajak duduk bersama. Dan dalam keheningan itu, kemanusiaan mulai perlahan-lahan terhapus dari narasi iman.
Di bawah bayang-bayang Tuhan, manusia sering hilang—bukan karena Tuhan menghilangkannya, tapi karena manusia terlalu sibuk berdiri di antara-Nya dan sesama. Kita menjadikan iman sebagai menara, bukan jembatan. Kita membangun tembok, bukan pelukan.
Namun belum terlambat untuk kembali. Belum terlambat untuk menyadari bahwa menyebut nama Tuhan tak cukup jika tidak diikuti dengan tindakan yang memuliakan ciptaan-Nya. Bahwa kebenaran yang tak membebaskan, bukanlah kebenaran yang utuh. Dan bahwa iman, jika tak membawa cinta kasih, hanyalah gema kosong yang memantul di dinding hati yang tertutup.